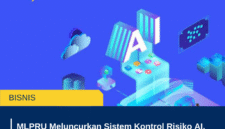Novel : Bertahan di Atas Luka Part 32
Amira Dzakiya
Aku sedang menyusun oleh-oleh untuk teman-teman di Riyadh ketika bel pintu berbunyi. Siang ini, seperti biasa rumah sepi karena aku hanya berdua dengan Ibu yang sedang beristirahat di kamar. Si kembar kerja dan baru akan pulang sore nanti. Perlahan aku berdiri menuju ruang tamu dan mengintip dari tirai jendela. Seketika aku mematung ketika mengetahu siapa yang datang. Jantungku seolah meloncat keluar. Cepat aku menutup kembali tirai jendela dengan tangan masih gemetar.
Untuk apa ia ke sini? Dari mana ia tahu kalau aku masih di Jakarta?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bel kembali berbunyi, menyadarkanku dari rasa terkejut.
Pelan aku membuka pintu. Sebetulnya, aku ingin pura-pura tidak mendengar dan membiarkan lelaki itu pergi karena mengira rumah kosong. Namun, aku khawatir Ibu terbangun dan heran kenapa aku tidak mau membuka pintu. Sambil menguatkan hati, kubuka pintu ruang tamu dan melihat sosok tinggi lelaki yang akhir-akhir ini wajahnya sering hadir dalam pikiranku.
“Assalamualaikum, Mir!”
Aku membalas salamnya sambil menelan ludah untuk membasahi kerongkongan yang tiba-tiba kering.
“Eh, Pras! Tumben …, ada angin apa, nih?”
“Ganggu nggak, Mir? Mau ngobrol-ngobrol aja. Aku dikasih tahu Marisa kalau kamu masih di Indonesia. Kita belum sempat ngobrol waktu di rumahnya, kan?”
“Oh …, nggak, kok. Duduk, deh!” ujarku mencoba bersikap biasa.
Tenang, Amira! Nggak usah panik dan gugup, dia hanya mau ngobrol. Jangan GR!
Pras tersenyum manis dan duduk di teras. Cuaca mendung dengan semilir angin yang sejuk membuat kami merasa nyaman walau duduk di luar. Apalagi, ada pohon kersen di halaman depan, menambah sejuk suasana siang itu. Aku duduk di kursi di seberang Pras. Aku sengaja menata kursi kayu di teras membentuk huruf L dengan meja kayu persegi panjang di tengah. Meskipun dari kayu, tapi dilengkapi dengan bantalan sofa supaya tetap empuk.
“Kapan kamu balik ke Riyadh?” Pras membuka percakapan.
“Insyaallah dua minggu lagi,” jawabku singkat.
Suasana terasa janggal dan membuat kami seperti kehilangan kata-kata.
“Oya, Pras … aku turut berduka cita, ya. Semoga Allah ampuni semua dosa-dosa Safira,” ucapku tulus.
Mata Pras terlihat berkaca-kaca.
“Makasih, Mir! Allah lebih sayang Safira. Nyesal banget kenapa waktu itu aku biarin Fira pulang sendiri, padahal biasanya aku selalu ikut kalau dia ada kerjaan di luar kota. Ketika itu kami pikir Bandung kan dekat, jadi Fira bisa nyetir sendiri. Aku tidak bisa mengantarnya karena kebetulan ada agenda ketemu klien di Jakarta pada hari yang sama,” tutur Pras dengan suara bergetar. “Andai saja waktu bisa diputar kembali, aku akan membatalkan pertemuan dengan klien dan ikut ke Bandung mendampingi Safira.”
“Kamu nggak boleh ngomong gitu, Pras. Semua udah takdir-Nya. Kita nggak pernah tahu hikmah apa yang Allah sedang siapkan untuk hidup kamu, tapi pasti yang terbaik. Allah memilihmu karena tahu kamu kuat dan sanggup menjalani ujian ini.
Pras menatapku penuh arti.
“Dari dulu kamu memang bijaksana dan selalu tahu cara menghibur orang lain. Kamu bisa membuat orang lain merasa tenang dan kuat menghadapi masalah. Bayu beruntung banget bisa dapetin kamu,” puji Pras terdengar tulus.
Aku tersipu. Andai saja kamu tahu masalah rumah tanggaku yang belum bisa aku selesaikan, kamu pasti nggak akan memujiku seperti ini, Pras. Andai saja suamiku sesekali memuji seperti kamu memujiku, rumah tangga kami pasti akan baik-baik saja.
“Jangan muji terlalu tinggi, ntar kalau jatuh sakit,” gurauku mencoba menutupi rasa kikuk. “Aku nggak seperti yang kamu pikir, Pras. Mungkin aku bisa menghibur dan menguatkan orang lain, tapi belum tentu aku bisa menghibur diri sendiri,” ujarku lirih.
Pras tersentak.
“Kamu baik-baik aja, Mir? Semuanya baik-baik aja, kan?” tanyanya penuh perhatian.
“Aku sama Bayu baik-baik, aja. Kalau ada pertengkaran kan lumrah dalam hubungan suami istri, nggak perlu dibesar-besarkan,” jawabku mengelak.
“Syukurlah kalau hubugan kamu sama Bayu baik-baik aja. Aku nggak rela kalau Bayu sampai nyakitin kamu.”
“Lho, kok kamu yang nggak rela?” tanyaku dengan kening berkerut. “Oh, karena kamu sahabatku, ya?” Aku berusaha bersikap biasa menghadapi Pras.
“Iya. Selain sahabat, kamu kan tahu kalau aku juga pernah menyukaimu.”
Aku tertegun, tidak menyangka Pras akan berbicara terus terang seperti ini.
“Nggak kok, aku dan Mas Bayu baik-baik, aja. Kami bahagia,” ujarku tersenyum. “Eh, sampai lupa. Mau minum apa, Pras?” Aku berdiri untuk mengusir rasa jengah yang muncul. Biar bagaimanapun aku adalah istri orang, tidak pantas rasanya bicara hal seperti ini dengan laki-laki lain.
“Apa aja boleh,” jawab Pras kalem.
Aku bergegas masuk untuk menata hati dan perasaanku. Perasaan berdosa menyergap. Bagaimana mungkin aku bermain api dengan laki-laki lain sementara aku masih berstatus sebagai istri?
Tapi kamu kan udah mau cerai, nggak ada salahnya membuka diri untuk lelaki lain. Pras itu sahabat lamamu, kamu udah tahu sifatnya. Ia sangat perhatian dan lembut. Kamu pasti nggak akan pernah merasa kecewa seperti sekarang, apalagi ia sangat mencintaimu. Bisikan setan terus menggema di hatiku, membuatku terlena sejenak, tapi segera kutepis.
Halaman : 1 2 Selanjutnya